
Yogyakarta, 12 September 2025 – Angkringan #25 yang diadakan oleh CICP kali ini mengangkat topik “Social and Clinical Discourse in Social Media: Komunitas Virtual dalam Memaknai NSSI di TikTok.” Diskusi kali ini menghadirkan Dea Siti Hafsha sebagai Tamu Super, dengan Azza Fahira Soebroto sebagai Among Tamu yang memandu jalannya acara.
Diskusi dibuka dengan mengangkat satu fenomena yang sedang marak di media sosial, yaitu Non-Suicidal Self Injury (NSSI) atau perilaku menyakiti diri tanpa tujuan untuk bunuh diri. Fenomena ini dinilai semakin sering muncul di dunia virtual, salah satunya di platform TikTok. Tidak hanya dalam bentuk konten, NSSI juga membentuk semacam komunitas virtual di platform tersebut, di mana para pengguna berbagi pengalaman dan perasaan terkait perilaku tersebut melalui kolom komentar.
Dea Siti Hafsha, melalui penelitian tesisnya, mencoba untuk memahami bagaimana komunitas virtual di platform TikTok memaknai perilaku NSSI. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan Social Network Analysis (SNA) untuk memetakan struktur hubungan pengguna TikTok dalam komunitas virtual NSSI. Dengan menganalisis 168 video yang relevan dan lebih dari 16 ribu akun pengguna beserta komentar-komentarnya, ditemukan 128 komunitas virtual dengan tingkat modularitas tinggi (0,906), menandakan struktur jaringan yang kuat dan kohesif.
Sebelum membahas temuannya, Dea memaparkan terlebih dahulu pengertian NSSI dan data-data terkait fenomena NSSI. Dea menjelaskan bahwa NSSI merupakan perilaku dimana individu melukai jaringan tubuh sendiri secara sengaja tanpa berniat untuk mengakhiri hidup. Secara sosial, perilaku ini tidak diterima masyarakat dan umumnya dilakukan secara tersembunyi.
Data menunjukkan bahwa 20–36,9% siswa di Indonesia pernah melakukan NSSI, dengan rentang paling tinggi di individu berusia 15–17 tahun. Cara yang umum digunakan adalah menyayat kulit (cutting/barcode), membenturkan kepala, mengganggu luka yang belum sembuh, serta mencakar, menggigit, dan membakar bagian tubuh tertentu. Selain itu, penelitian-penelitian menunjukkan bahwa meskipun NSSI dilakukan tanpa niat mengakhiri hidup, perilaku ini kerap menjadi salah satu prediktor perilaku bunuh diri di kemudian hari.
Dea juga menyoroti bahwa istilah “barcode” menjadi populer setelah munculnya sebuah lagu bertema NSSI dari Korea Selatan. Lagu ini, yang sempat viral di berbagai platform, dinilai menormalisasi perilaku self-harm dan bahkan memicu peningkatan yang signifikan terhadap jumlah kasus kunjungan UGD terkait NSSI di negara asalnya tersebut.
Secara klinis, NSSI dipertahankan bukan semata karena adanya faktor risiko, melainkan oleh fungsinya yang dirasakan oleh individu. Fungsi intrapersonal seperti regulasi emosi, anti-disosiasi, dan self-punishment merupakan yang paling dominan. “Sakitnya NSSI dipercaya dapat mengurangi intensitas beban emosi,” jelas Dea. Selain itu fungsi interpersonal seperti autonomy, peer bonding, dan interpersonal boundaries turut berpengaruh dalam keberlangsungan perilaku.
Oleh karena NSSI dipandang negatif di masyarakat, individu yang melakukan NSSI biasanya berusaha menyembunyikan bekas-bekas lukanya apabila ada dan tidak membicarakan perilakunya tersebut sembarangan. Di sisi lain, individu-individu tersebut tetap memiliki keinginan untuk menyalurkan emosi dan pengalamannya, termasuk juga perilaku NSSI-nya. Dalam hal ini, sosial media berperan layaknya tempat pelarian individu-individu tersebut. Ruang digital seperti platform TikTok memberikan wadah bagi individu untuk menyalurkan emosi tanpa merasa takut dihakimi.
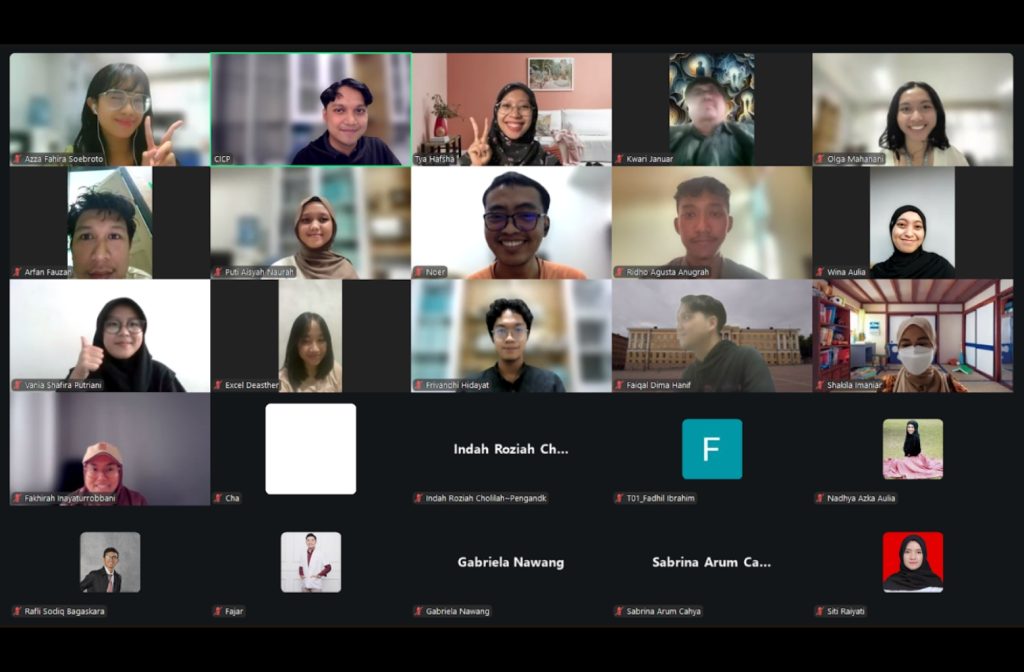
Dea kemudian lanjut mengulas bagaimana proses pembentukan komunitas virtual NSSI. Komunitas virtual terbentuk melalui proses social sharing of emotion, dimana seseorang terdorong untuk membagikan pengalaman emosionalnya di media sosial, memicu secondary sharing dari pengguna lain yang merasa terhubung secara emosional. Hasilnya, muncul jejaring yang erat antarindividu dengan pengalaman serupa. Fenomena ini juga dapat dipahami melalui konsep homophily, yaitu kecenderungan manusia untuk berinteraksi dengan individu lainnya yang memiliki pengalaman serupa. Dalam konteks TikTok, proses tersebut berlangsung di kolom komentar dari video-video yang viral dan masuk ke fyp pengguna lainnya.
Melalui analisis tematik yang dilakukan, Dea menemukan salah satu tema dominan dalam percakapan komunitas ini: “Gagal berhenti karena cuma itu yang membuat tenang.” Temuan tersebut mencerminkan bahwa bagi sebagian pelaku, NSSI berperan sebagai bentuk mekanisme koping emosional.
Dalam bagian diskusi penelitiannya, Dea menekankan bahwa pembentukan komunitas virtual NSSI sebenarnya lebih ditentukan oleh algoritma TikTok daripada figur influencer. Ia menyebut fenomena ini sebagai bentuk “community woven by algorithm”, yaitu komunitas yang tidak terpusat, tanpa pengawas, dan tanpa batas struktural, tetapi terbentuk karena algoritma TikTok yang mempertemukan individu-individu dengan ketertarikan serupa.
Terakhir, Dea menutup pemaparannya dengan refleksi kritis: komunitas-komunitas ini memperlihatkan dua sisi: di satu sisi, menjadi ruang ekspresif bagi individu yang berjuang dengan rasa sakitnya; namun di sisi lain, juga berpotensi menormalisasi dan memperkuat perilaku berisiko.
Melalui Angkringan #25 ini, peserta diajak untuk memandang NSSI tidak hanya sebagai fenomena klinis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh keberadaan ruang digital. Kehadiran sosial media memungkinkan munculnya komunitas virtual yang turut memengaruhi cara individu memaknai, mengekspresikan, bahkan menormalisasi pengalaman NSSI. Perspektif ini membuka ruang refleksi tentang bagaimana teknologi membentuk interaksi dan kondisi psikologis individu-individunya.
